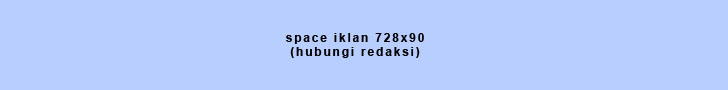Oleh: Ali Rahman
Dosen FH Universitas Sawerigading Makassar
SIMPULINDONESIA.com_ Konfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status tersangka mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2023–2024 membuka kotak pandora regulasi perhajian kita.
Titik apinya adalah pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah yang dibagi rata (50:50) antara haji reguler dan haji khusus. Namun, jika diskursus hanya berhenti pada perdebatan angka 92:8 versus 50:50, kita hanya menyentuh permukaan.
Akar persoalannya jauh lebih serius: kualitas norma dan desain kewenangan yang masih "abu-abu".
Celah Norma: Benturan Pasal 64 dan Pasal 9
UU Nomor 8 Tahun 2019 memuat dua perangkat normatif yang kuat tetapi tidak sepenuhnya sinkron saat berhadapan dengan "kuota tambahan".
• Pasal 64 secara rigid menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.
• Pasal 9 mengatur bahwa jika terdapat penambahan kuota setelah penetapan nasional, pengisiannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.
Di sinilah muncul ruang tafsir: Apakah frasa “kuota haji Indonesia” otomatis mencakup total kuota tahun berjalan (termasuk tambahan), sehingga formula 8% bersifat mengikat mati? Ataukah kuota tambahan merupakan rezim kondisional (discretionary power) yang memberi ruang bagi Menteri untuk mengatur komposisinya demi kepentingan darurat? Tanpa definisi operasional yang tegas, kedua tafsir ini akan terus berbenturan.
Keselamatan sebagai 'Policy Gate'
Pemerintah kerap memosisikan keselamatan sebagai alasan kebijakan. Kepadatan di Mina, keterbatasan tenda, dan ketersediaan fasilitas sanitasi adalah persoalan riil di lapangan. Kuota tambahan yang datang menjelang keberangkatan menuntut penyesuaian logistik yang ekstrem dalam waktu singkat.
Dalam hukum, prinsip necessity (kebutuhan mendesak) dapat menjadi mekanisme pembatas. Namun, ia menuntut syarat: ancaman harus terukur, tindakan harus proporsional, dan alasan harus transparan serta dapat diaudit.
UU 8/2019 sendiri menyediakan "kompas" melalui Pasal 2 yang memuat asas kemaslahatan, kemanfaatan, dan keselamatan. Tiga asas ini bukan sekadar ornamen teks. Jika pemerintah mengubah komposisi kuota demi keselamatan, alasan tersebut harus lolos uji substantif: Apakah perubahan itu benar-benar meningkatkan keselamatan jemaah secara nyata, atau hanya dalih administratif?
Hukum untuk Manusia
Kritik Satjipto Rahardjo terhadap legalisme sangat relevan di sini. Hukum bukanlah teks beku; orientasinya harus pada keadilan substantif. Ungkapan "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" mengingatkan kita agar kebijakan tidak menjadi ritual prosedural yang justru mengorbankan keselamatan dan keadilan jemaah yang telah mengantre puluhan tahun.
Pembagian 50:50 yang diperdebatkan semestinya dibaca sebagai bentuk implementasi strategis. Jika memang alasan keselamatan dan daya tampung maktab di Saudi lebih memungkinkan bagi skema haji khusus pada saat itu, maka kebijakan tersebut merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan jemaah.
Jalan Keluar: Rekonstruksi dan Penjernihan
Untuk memutus mata rantai sengketa kebijakan yang berulang setiap musim haji, diperlukan dua langkah strategis:
- Pertama, Penegasan Yurisdiksi Norma. Perlu ditegaskan apakah angka 8% pada Pasal 64 mengikat total kuota nasional secara agregat atau hanya kuota dasar. Ini penting untuk memperkuat kepastian hukum bagi penyelenggara.
- Kedua, Uji Konstitusional. Mengingat adanya ketidakjelasan rumusan antara Pasal 64 dan Pasal 9, pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK) layak dipertimbangkan.
Langkah ini bukan untuk menghapus akuntabilitas, melainkan untuk mencari "makna konstitusional" yang final agar kebijakan di masa depan tidak lagi berujung pada kriminalisasi akibat ambiguitas norma.
Pada akhirnya, haji bukan sekadar urusan angka dan kuota, melainkan pemenuhan hak ibadah yang harus dipayungi oleh hukum yang jelas dan berpihak pada keselamatan manusia.